Dukungan Sumber Daya bagi OMS (7/12)
Seri 1/2 dari Bag. 3 Tantangan Abad ke-21, dari keseluruhan 12 seri artikel berjudul Menuntaskan Dilema “Moral dan/atau Modal?” dalam Praksis Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia, ditulis oleh Hasan Bachtiar.
Keterangan lengkap tentang tulisan ini.
Memasuki milenium baru, abad ke-21, OMS di Indonesia—juga di hampir seluruh negeri Dunia Ketiga—menghadapi suatu masa depan baru yang lebih rumit. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Konteks makro-ekonomi-politik yang termutakhir, yakni berkuasanya rezim Neo-Liberal yang mengendalikan tata dunia melalui perjanjian-perjanjian politik, sosial, hukum, dan ekonomi dalam wadah UN dan WTO, seperti sudah diurai panjang-lebar di atas, adalah suatu tantangan nan mahaberat yang sudah di depan mata.
Masalah lainnya berasal dari sisi internal pengelolaan dan keberlanjutan hidup OMS, khususnya dalam aspek dukungan sumber daya (resources). Memang benar bahwa ada banyak jenis sumber daya, misalnya manusia, informasi, peralatan dan bahan, tetapi “uang” adalah sumber daya terpenting—seperti dikatakan Alex Jacobs dalam lampiran buku Handbook Manajemen Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil, uang seibarat “darah”—bagi OMS. Kerapkali uang dan pendanaan menjadi isu yang paling panas. Semakin lama semakin nyata dirasakan bahwa jumlah bantuan keuangan (financial aid), khususnya yang berasal dari lembaga-lembaga donor asing (publik atau negara maupun swasta), semakin menipis. Padahal, dana donor inilah yang, selama ini, menjadi sumber utama—kalau bukan, bahkan, sumber “satu-satunya”—bagi OMS Indonesia untuk membiayai pelbagai proyek pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, konsekuensi logisnya, meningkatlah persaingan di antara OMS-OMS untuk memperebutkan sumber daya keuangan tersebut. Masalah ini, ternyata, terjadi tidak secara terpisah namun bertali-temali dengan isu-isu efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses serta hasil kerja OMS.
Alan Fowler menyebut situasi semakin terbatasnya dukungan sumber dana bagi OMS ini sebagai “skenario pasca-bantuan” (beyond-aid scenario, atau skenasio melampaui-bantuan). Fowler mengidentifikasi beberapa sebab yang melatarbelakanginya. Sejak awal dekade 1990-an, muncul kekecewaan dari para donor bahwa dana-dana bantuan yang selama ini mereka hibahkan kepada OMS telah diimplementasikan secara tidak efisien, tidak efektif, bahkan banyak yang diselewengkan untuk memperkaya para pekerja OMS sendiri. Demikianlah, kalangan OMS telah tampil dengan suatu “poor performance and loss of credibility”. Meskipun berjumlah keseluruhan sekira US$ 1,5 triliun pada tahun 1998, sejak tahun 1991, sesungguhnya, nilai bantuan yang nyata dari Utara ke Selatan telah menurun sekira 21%. Tidak seluruhnya dari jumlah itu toh dinikmati warga miskin di Selatan.
Tambahan lagi, para donor semakin memfokuskan penyaluran dana bantuannya hanya kepada “negeri-negeri yang benar-benar menderita kemiskinan yang akut”, dan “mereka ingin membuat perubahan yang berarti sekaligus cepat”, seperti di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Kondisi ini, suatu “kompetisi memperebutkan dana donor internasional”, lantas menciptakan “pemenang vs. pecundang”—setelah sebelumnya merebak isu tentang “oligopoli akses donor” oleh para “aktivis-senior”, yang dianggap memegang trust—dalam kalangan masyarakat sipil sendiri. Dengan demikian, bagi negeri-negeri Selatan yang sudah dianggap relatif mampu survival, Indonesia salah satunya, wilayah Amerika Latin, serta Newly Industrialized Countries (NICs) lainnya, mekanisme “hibah bantuan kemanusiaan” (humanitarian grant aids) bakal diubah menjadi “investasi asing langsung” (foreign direct investment). Maka, tak mengherankan bila Fowler menduga bahwa “agenda implisit” bantuan pembangunan internasional di bawah skema globalisasi ekonomi Neo-Liberal telah “bergeser”: dari “melayani kepentingan-kepentingan Perang Dingin lama” menjadi “mengakselerasi penetrasi pasar”—entah melalui gender mainstreaming, good governance, political decentralization, deregulasi-privatisasi, dst.
Selain itu, tampaknya, masih terlalu sedikit jumlah OMS yang berhasil mengadakan dan mengelola unit-unit usaha (business units) sebagai sumber dana mandiri untuk membiayai program-program layanannya. Keadaan ini diperparah dengan belum tergarapnya potensi filantropi nasional—yang konon, menurut studi PIRAC, masih cukup besar. Sebab yang lebih mendasar ialah, pada hemat saya, publik Indonesia masih menyumbangkan dana-dana amalnya (charity) secara sporadis belaka, terutama kepada lembaga-lembaga agama ataupun pada saat terjadi bencana alam. Menyumbang kepada sebuah OMS secara rutin belum lazim. Pendek kata, publik Indonesia belum mengenal konsep “development” secara lebih tepat.

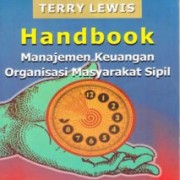









 lingkarLSM.com
lingkarLSM.com PENABULU ALLIANCE
PENABULU ALLIANCE KOMUNITAS KEUANGAN LSM
KOMUNITAS KEUANGAN LSM KYUTRI KELAS BERBAGI
KYUTRI KELAS BERBAGI RUMAH KEMUNING
RUMAH KEMUNING