Tantangan Pertama: Legitimasi Politis
Dalam tiga tahun terakhir ini LSM kita, setidaknya sebagian, cenderung dan sudah memainkan peran politik. Modus yang kini banyak dipilih oleh LSM dalam “berpolitik” adalah dengan membentuk koalisi: koalisi perempuan, koalisi kebebasan informasi, koalisi undang-undang yayasan, koalisi kebijakan public, dan yang paling mutakhir koalisi konstitusi baru. Cara ini dipilih agaknya untuk mencari sinergi dan merapatkan barisan hingga daya desaknya menguat. Mereka mencoba melakukan advokasi untuk mempengaruhi jalannya pengambilan keputusan. Tapi, soalnya adalah bagaimana meletakkan posisi dan mengatur peran politik LSM ini dalam sistem politik kita hingga partisipasinya bermakna.
Kiprah puluhan LSM dalam wawancara kebijakan publik diatas memang menampakan peran politik LSM seolah telah berarti. Tapi itu dipermukaan saja. Actor yang memiliki legitimasi politik serta bias mengklaim mewakili rakyat jelas hanya partai politik. Akibatnya, meski banyak kalangan LSM berkompetensi teknik merumuskan berbagai rancangan kebijakan politik dengan segala pilihan posisi politiknya kerja keras mereka tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kalau ya, berarti perkecualian, karena memang tidak ada keharusannya. Sebaliknya, acap kali nama LSM justru dicatut oleh para politisi dan birokrat kita untuk mengabsahkan keputusan mereka sendiri.
Mengapa itu terjadi? Jawabnya adalah karena tidak adanya legalitas yang merupakan prasyarat penting bagi keabsahan proses partisipasi. Tanpa legalitas formal, pendapat, pikiran, dan berbagai masukan LSM itu tak memiliki legitimasi dan status politis, apalagi hokum, yang mengharuskan pengambil keputusan mempertimbangannya. Secara normative dalam menyusun undang-undang misalnya, baik pemerintah maupun DPR, memang perlu melakukan konsultasi, sebagaimana diatur dalam Keppres No 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang. Istilah “forum konsultasi” dalam Keppres ini mangacu pada tiap tahap penyusunan RUU, mulai dari naskah akademik sampai rumusan yang siap diajukan kepada DPR. Tata Tertib DPR RI pun menggunakan istilah konsultasi, dan mengatur sejumlah rapat dan kepanitiaan yang memberi kesempatan kelompok masyarakat untuk berpatisipasi dalam penyusunan kebijakan. Tapi, semuanya dalam batas “dapat” dan bukan “harus” menyelenggarakannya. Pada tata tertib di tingkat DPRD kata konsultasi bahkan tidak dapat ditemukan.
Karena itu salah satu langkah yang penting diambil adalah pembuatan dan penerapan tata cara berpatisipasi secara formal. Kelompok-kelompok masyarakat, termasuk LSM, perlu mendapatkan suatu status resmi dalam proses penyusunan kebijakan; agar masukan, pandangan dan pikiran mereka, dapat dituangkan dalam suatu kertas posisi yang berstatus jelas. Berkaca pada Filipina, keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses politik dan pengambil keputusan ini bahkan diberi pengakuan konstitusioanal. Konstitusi 1986 Filipina, dalam Artikel II Seksi 23 dan Artikel XIII Seksi 15 dan 16, secara jelas memandatkan Negara untuk meningkatkan peran, menyediakan saran politik dan hukum, serta menyelenggarakan konsultasi, bagi organisasi masyarakat, termasuk LSM.
Maka, LSM kita saaat ini pertama-tama perlu mengagendakan ketersediaan platform politik dan hukumnya tersebut. Setidaknya ada dua hal yang perlu diadvokasikan untuk melembagakan peran politik LSM secara legitimate.
Pertama, diadakannya kerangkan dan produk hukum yang mengatur masalah hak, kewajiban, prosedur dan mekanisme partisipasi organisasi non-pemerintah. Kerangkan hukum ini diperelukan untuk memberikan keabsahan dan legitimasi politis bagi kelompok non-pemerintah (dan DPR) di satu pihak, serta batasan akan hak, kewajiban, dan kewenangan mereka di lain pihak.
Kedua, diadakannya tata cara, prosedur, serta mekanisme berpartisipasi sebagai petunjuk teknis dan panduan, baik bagi kelompok non-pemerintah maupun pemutus kebijakan. Tercakup dalam panduan teknis ini kriteria untuk pemberian status bagi suatu kelompok yang relavan dengan subtansi kebijakan tertentu yang sedang disusun. Melekat dalam status tersebut hak dan kewenangan masing-masing kelompok sesuai dengan batas-batas yang diberikan oleh peraturan perundangan yang telah ditetapkan.
Tanpa instrument politis, hukum dan teknis di atas, peran politik LSM kita akan selalu semu. Suaranya boleh jadi akan terdengar semakin keras, tetapi pengaruhnya tidak seberapa. Para politisi dan birokratlah yang akan terus menguasai secara bebas arena pengambilan keputusan dan kebiajakan public. Dalam konteks ini perjuangan untuk merumuskan TCP3 (Tata Cara Penyusunan Peraturan Perudang-undangan) yang partisipatif sangatlah penting.
Disarikan dari buku: Kritik & Otokritik LSM, Editor: Hamid Abidin, Mimin Rukmini, Hal: 24-26.

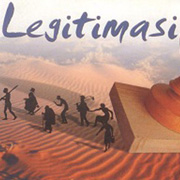









 lingkarLSM.com
lingkarLSM.com PENABULU ALLIANCE
PENABULU ALLIANCE KOMUNITAS KEUANGAN LSM
KOMUNITAS KEUANGAN LSM KYUTRI KELAS BERBAGI
KYUTRI KELAS BERBAGI RUMAH KEMUNING
RUMAH KEMUNING