Aturan Main OMS yang Terkait (12/12)
Seri 3/3 dari Bag. 5 Manajemen Keuangan OMS ala Indonesia, dari keseluruhan 12 seri artikel berjudul Menuntaskan Dilema “Moral dan/atau Modal?” dalam Praksis Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia, ditulis oleh Hasan Bachtiar.
Keterangan lengkap tentang tulisan ini.
Isu lain yang juga tak kalah signifikan dalam membentuk gaya sistem manajemen keuangan OMS Indonesia adalah “aturan main” resmi yang berlaku, yakni hukum atau perundang-undangan di Indonesia. OMS Indonesia, sudah jelas, menyadari pentingnya penegakan aturan hukum (law enforcement), sebagaimana halnya isu ini telah menjadi kepedulian OMS yang terimplementasikan melalui banyak cara: kampanye penyadartahuan hukum kepada warga negara, inisiasi perumusan aturan hukum (legal drafting dan counter-legal drafting), pengawasan terhadap kinerja negara dalam menegakkan hukum melalui aparat-aparatnya (kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dll.), revitalisasi hukum dan komunitas adat, hingga gerakan massa untuk melaksanakan kritik dan advokasi.
Perangkat hukum terutama dan termutakhir yang memayungi kiprah OMS Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan—yang terdiri atas 14 bab dan 73 pasal, disahkan pada tanggal 6 Agustus 2001, tiga tahun setelah “reformasi”. Beberapa segi khusus dari UU 16/2001 ini perlu dibahas sebentar di sini—karena setiap “karakter produk hukum ditentukan oleh konfigurasi politik” yang sedang berlangsung, khususnya ideologi kelas dominan yang tengah berkuasa (ideology of the dominant, ruling class).
UU 16/2001 hanya mengatur bentuk badan hukum “yayasan”, yang didefinisikan sebagai “badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota” (Pasal 1). Kemudian, UU ini menetapkan bahwa “organ yayasan” (Bab VI) adalah “pembina” (Pasal 28—30), “pengurus” (Pasal 31—39), dan “pengawas” (Pasal 40—47). Setiap yayasan juga diwajibkan untuk menyusun “laporan tahunan” (Bab VII), yang berupa “laporan keadaan dan kegiatan” dan “laporan keuangan” (Pasal 49). Sebagaimana sudah dibahas di atas, sesuai PSAK No. 45, laporan keuangan yayasan dalam UU 16/2001 adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan keuangan yayasan “wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia” dam “wajib diaudit oleh Akuntan Publik” apabila jumlah bantuan yang diperoleh yayasan sebesar Rp500 juta atau lebih dan “mempunyai kekayaan di luar harta wakaf” sebesar Rp20 miliar atau lebih.
Apa yang menjadi poin kritis dari UU 16/2001, menurut kalangan OMS Indonesia, adalah hal-ikhwal perpolitikan di baliknya. UU 16/2001 lahir, menurut debat publik yang berlangsung segera setelah terbitnya UU ini, sekira pada akhir 2001, sebagai respon terhadap penyelewengan-penyelewengan yang pernah dilakukan oleh yayasan-yayasan yang didirikan oleh Soeharto, penguasa “rezim neo-fasis militer” Orde Baru. Soeharto mendirikan begitu banyak yayasan, yang melibatkan pula begitu banyak petinggi militer (TNI-AD, AL, AU, dan Polri), Golkar, serta konglomerat-konglomerat kroni, yang kemudian terbukti menjadi mesin “pencucian uang” (money laudering) triliunan rupiah hasil korupsi selama lebih dari tiga dekade.
Diresmikannya UU 16/2001 seolah-olah menjadi “pukulan balik” (backlash) bagi OMS-OMS, selain yayasan-yayasan Soeharto, yang selama Orde Baru sudah serius dan gigih menggerakkan demokratisasi. OMS Indonesia merasa cuma menerima getah tanpa ikut menikmati hasil korupsi tadi. Maka, di satu sisi, UU 16/2001 merupakan jalan awal bagi pemerolehan suatu kepastian payung hukum bagi OMS, sekaligus akomodasi sektor ketiga dalam wacana dan praktik kenegaraan; di sisi lain, UU tersebut dituding sebagai tak lebih dari alat negara untuk “menyeragamkan” keanekaragaman sekaligus “mengendalikan” kritisisme-radikal OMS!
Suatu kenyataan yang lain, OMS Indonesia berdiri dan berkiprah dalam bentuk lembaga yang bermacam-macam, bukan cuma yayasan, lingkup operasinya berbeda-beda, susunan pengelolaannya juga dibentuk dan disebut dengan beraneka cara, bahkan menerapkan sistemmanajemen keuangan yang juga beraneka ragam! Dengan begitu, keanekaragaman OMS Indonesia tidak terakomodasi secara meyakinkan dalam UU 16/2001. Suatu siasat respon balik pun diberikan OMS dengan cara mendaftarkan status hukum kelembagaannya sebagai “perkumpulan/perhimpunan”.
Soal “perpajakan” (taxation) adalah giliran berikutnya. Kalau OMS Indonesia sudah jelas ingin menaati hukum, maka kalangan OMS Indonesia juga ingin melihat negara yang menaunginya “kuat”, dalam artian stabil dan birokrasinya mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang memuaskan bagi warga negara. Untuk mewujudkan itu, saya yakin bahwa OMS Indonesia bersedia membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku resmi.24 Namun, sudah menjadi rahasia umum, iklim perpajakan di Indonesia tidak mendukung tumbuh-kembangnya sektor ketiga. Di Indonesia belum berlaku kebijakan “pengurangan pajak” (tax deduction) seperti di Amerika Serikat, misalnya, yang terbukti cukup efektif dalam merangsang minat kaum berpunya pelaku sektor bisnis untuk menyumbangkan sebagian keuntungan bisnisnya bagi program-progran pelayanan kemanusiaan melalui OMS. Akibatnya, kebijakan perpajakan di negara ini tidak memungkinkan OMS Indonesia menggali sumber-sumber pendanaan dari publik nasional, sehingga membuat OMS Indonesia selalu bersusah-payah melakukan outsourcing ke luar negeri. Tuduhan nyinyir yang selalu memojokkan OMS Indonesia sebagai “didanai asing dan bekerja demi kepentingan asing” menjadi risiko yang tak terpecahkan hingga kini. Padahal, yang membuat OMS Indonesia tidak “mandiri”, tidak lain tidak bukan, adalah bangsanya sendiri!

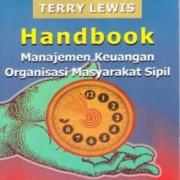









 lingkarLSM.com
lingkarLSM.com PENABULU ALLIANCE
PENABULU ALLIANCE KOMUNITAS KEUANGAN LSM
KOMUNITAS KEUANGAN LSM KYUTRI KELAS BERBAGI
KYUTRI KELAS BERBAGI RUMAH KEMUNING
RUMAH KEMUNING